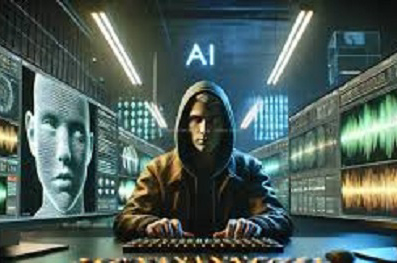LESINDO.COM – Di era digital kini, jarak seakan kian mengecil. Komunikasi masa-nyata, akses instan, dan teknologi canggih membuat dunia terasa seperti satu ruang terbuka tanpa sekat. Namun, di balik kecepatan dan kemudahan itu, muncul dilema besar: ketika kenyataan dan tipuan hampir tak bisa dibedakan. Teknologi menyajikan dua wajah di satu sisi, ia membawa kemaslahatan bersama: informasi bisa tersebar cepat, edukasi terbuka, komunikasi melintasi benua. Namun di sisi lain, ia juga bisa menjadi media manipulasi: rekayasa digital, konten yang tampak nyata padahal direkayasa, kesalahan yang dibalut sebagai kebenaran.
Pisau Bermata Dua Bernama Teknologi
Teknologi, sebagaimana pisau, bisa bermanfaat untuk kebaikan — namun juga berbahaya bila disalahgunakan. Kecerdasan buatan (AI), misalnya, mampu membantu pekerjaan manusia dengan cepat dan akurat, tapi juga dapat menciptakan deepfake, suara palsu, bahkan wajah digital yang meniru seseorang secara sempurna. “Sekarang ini banyak konten yang secara visual meyakinkan, tapi setelah dicek ternyata hasil rekayasa AI. Sayangnya, masyarakat sering mempercayai yang tampak nyata,” ujar Sri Mulyani, dosen Ilmu Komunikasi di salah satu perguruan tinggi di Surakarta, saat ditemui di sela kegiatan literasi digital, Senin (21/10).
Menurut Sri, tantangan terbesar di era digital bukan lagi soal keterbatasan akses informasi, tapi kemampuan menyaring informasi. “Kita sedang dibanjiri informasi, tapi tidak semuanya bernilai kebenaran,” tegasnya.
Data yang Membuka Mata
Fakta di lapangan mendukung kekhawatiran itu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat lebih dari 15.000 konten hoaks beredar di Indonesia selama tahun 2024, dengan peningkatan signifikan menjelang masa pemilu. Sebanyak 87 persen di antaranya tersebar melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X (Twitter). Sementara itu, hasil survei GeoPoll 2025 menyebutkan 76 persen pengguna internet di Indonesia menerima informasi dari media sosial sebagai sumber utama, dan lebih dari 40 persen mengaku tidak sempat memverifikasi kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain.
Di tingkat lokal, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surakarta melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 32 kasus penyebaran berita palsu yang melibatkan pengguna di Solo Raya. Mayoritas berupa berita manipulatif terkait politik, kesehatan, dan isu sosial. “Orang sekarang mudah percaya karena visualnya meyakinkan. Padahal, dengan teknologi AI, semua bisa direkayasa. Tantangannya bukan hanya tahu teknologi, tapi tahu etikanya,” jelas Ariyanto Budi Susetyo, pengamat dan penggiat media sosial.
Kenyataan yang Semu
Ironisnya, semakin maju teknologi, semakin kabur batas antara kebenaran dan kepalsuan. Foto, video, bahkan rekaman suara kini bisa dimanipulasi sedemikian rupa hingga tampak autentik. Di media sosial, misalnya, pernah viral video seorang tokoh publik berbicara kasar — padahal setelah diselidiki, video itu adalah hasil deepfake yang dibuat dengan perangkat AI generatif.
“Kalau orang awam yang lihat, pasti langsung percaya. Padahal itu bukan kenyataan,” ujar Rina Wulandari, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) yang aktif dalam komunitas literasi digital Gali Fakta Solo.
Ia menambahkan, komunitasnya rutin mengadakan pelatihan literasi media agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi digital. “Kami ajarkan cara fact-checking sederhana. Minimal, orang bisa tahu mana berita yang layak dipercaya.”
Kembali ke ‘Zaman Batu’?
Ungkapan “kembali ke zaman batu” bukan berarti manusia akan hidup tanpa teknologi, tetapi menggambarkan kondisi ketika peradaban kehilangan pegangan pada nilai dan kebenaran. Dunia boleh semakin canggih, tapi jika manusia tak bisa lagi membedakan nyata dan palsu, maka sesungguhnya kita mundur ke masa gelap. Teknologi seharusnya membuat manusia lebih cerdas, bukan lebih mudah tertipu.
“AI itu bukan musuh, tapi alat. Yang penting adalah manusianya: apakah ia mau berpikir kritis atau tidak,” tambah Sri Mulyani.
Menjadi Pengguna yang Cerdas
Beberapa langkah sederhana bisa dilakukan masyarakat untuk menghindari jebakan informasi palsu:
- Periksa sumber berita. Pastikan berasal dari media kredibel dan bisa diverifikasi.
- Jangan hanya baca judul. Banyak hoaks disebarkan lewat judul provokatif yang tidak sesuai isi.
- Gunakan fitur cek fakta Kominfo di situs cekfakta.kominfo.go.id.
- Ikuti pelatihan literasi digital. Di Solo, pelatihan semacam ini rutin diadakan di sekolah dan komunitas.
- Pikir dulu sebelum share. Jangan sampai jempol lebih cepat daripada akal sehat.
Kebenaran Tak Bisa Digantikan Teknologi
Teknologi memang membuat dunia semakin kecil, tapi juga membuat kebenaran semakin mahal. Dalam derasnya arus informasi, manusia perlu kembali ke hal yang paling mendasar: kesadaran berpikir, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral. Karena pada akhirnya, AI tidak bisa menggantikan nurani. Dan kebenaran — betapapun samar dalam dunia digital — tetap harus diperjuangkan oleh manusia yang berakal dan beretika. (Cha)