LESINDO.COM – Dulu, sekitar tahun 1991, saat masih berseragam SMA, aku pernah bermimpi menjadi seorang jurnalis. Profesi yang tampak begitu bebas: bisa pergi ke mana saja, bertemu siapa saja—dari pejabat, penjahit, hingga penjahat. Tak ada sekat dalam berkomunikasi. Rasanya seperti menjadi jembatan antara orang-orang yang berselisih, mencoba menengahi lewat tulisan yang berangkat dari balik “katanya”. Dari sanalah aku banyak belajar tentang sisi manusia—betapa luasnya perbedaan, betapa rumitnya watak, dan betapa dalamnya pelajaran hidup dari setiap pertemuan.
Dalam perjalanan waktu, aku melihat bahwa dunia ini selalu memiliki dua sisi. Ada siang dan malam, terang dan gelap, laki-laki dan perempuan. Begitu pula kehidupan—selalu ada pilihan. Tinggal kita mau memilih yang mana.
Watak, kata orang-orang tua di warung kopi, “tidak bisa diobati, tapi batuk bisa.” Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Watak adalah bawaan, sesuatu yang sudah terinstal sejak lahir, diturunkan dari gen orang tua, bahkan bisa melompat dari leluhur jauh di atas sana. Sedangkan karakter, ia dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman.
Ah, kalau sudah membahas watak dan karakter manusia, urusannya bisa panjang. Bisa-bisa malam habis untuk membedah literatur dan pendapat para ahli.
Memasuki tahun 2000, dunia media mulai berubah. Masa transisi datang begitu cepat. Wartawan menjadi profesi yang keren, bergengsi, seolah simbol orang cerdas. Padahal menurutku, pintar itu soal kemauan belajar. Setiap orang sudah dibekali kelebihan oleh Sang Pencipta; tinggal bagaimana mengasahnya.
Menjadi jurnalis memang menantang—setiap hari bertemu orang baru, suasana baru, persoalan baru. Tiap perjumpaan membuka jendela ilmu. Mau tak mau, jurnalis belajar memahami banyak hal sekaligus, dari ruang sempit konflik hingga lapang pandang kehidupan.
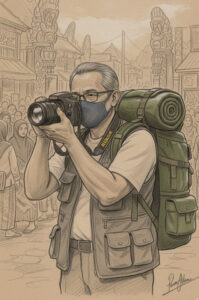
Namun, seiring perkembangan teknologi, dunia jurnalistik berubah arah. Media cetak terkena hantaman paling keras—seperti disapu tsunami yang datang tiba-tiba. Tak sepenuhnya mati, tapi sudah bukan masa jayanya lagi. Kini, hampir setiap orang bisa menjadi “jurnalis” lewat gawai di tangan. Setiap detik bisa siaran langsung tanpa sensor—entah benar, entah salah. Padahal, dalam kaidah jurnalistik, kebenaran bukan hanya soal fakta, tapi juga soal tanggung jawab moral.
Pelajaran terbesar menjadi bagian dari dunia jurnalistik adalah kehati-hatian. Dulu, kami dididik untuk selalu mematuhi rambu-rambu pers. Kini, semua terasa longgar—nyaris tanpa pagar. Tiap hari kita disuguhi informasi dari sumber yang tak jelas. Maka, kalau pun tidak tahu pasti, paling tidak kita perlu memeriksa ulang kebenarannya.
Banyak orang tertipu karena kebebasan informasi yang berseliweran di media sosial. Karena itu, pegangan paling aman adalah media yang masih berpegang pada kode etik jurnalistik. Meski ironisnya, tak sedikit juga media besar yang tergoda mengejar rating—semakin gaduh berita, semakin tinggi angka penonton. Dan sayangnya, sebagian orang memang menjadi penikmat pertikaian.
Ibarat menyaksikan rumah tangga tetangga yang sedang bertengkar—kita cukup melihat dari jauh. Jangan ikut campur, karena kita tak tahu dapurnya seperti apa. Niat baik kadang justru membawa ke pusaran masalah.
Bagiku, di tengah derasnya arus informasi yang tanpa batas ini, sikap paling bijak adalah berhati-hati. Tak perlu ikut larut, cukup nikmati secukupnya. Bila terasa berlebihan, ya sudahlah—kita hanya bisa berdoa.
Pada akhirnya, kita hanyalah masyarakat kecil yang berusaha tetap waras di tengah riuh dunia yang makin kehilangan sensor. (mac)


